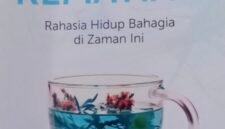Konsep negara Hobbes ini merupakan jawaban atas perkembangan baru di Eropa pada masa itu. Pada abad ke-17 terjadi perubahan radikal dalam sejarah filsafat politik. Revolusi konsep tentang dunia dan pandangan tentang manusia moderen berimbas pada konsep tentang filsafat politik. Pergeseran paradigma dan model-model baru refleksi dan lagitimasi politik menjadi urgen.
Filsuf Anglosaxon, Thomas Hobbes, membaca fenomen ini dan memberi tanggapan dengan meletakkan fundamen baru filsafat politik. Dalam karyanya De Cive (1642) dan Leviathan (1651), Hobbes mengembangkan sebuah konsep filsafat yang individualistis. Filsafat ini berpijak pada program rasionalitas ekonomis yakni maksimalisasi profit. Filsafat politik Hobbes bertolak belakang dengan filsafat politik Aristoteles serta seluruh teori politik pada Abad Pertengahan. Dengan metode analitis dan konsep pengetahuan generatifnya, Hobbes membersihkan aroma aristotelisme dari etika dan politik. Hukum kodrat Kristiani pun semakin menjauh dari disiplin filsafat.
Pemikiran Hobbes ini telah menjerumuskan Eropa ke dalam krisis tradisi yang maha dahsyat. Salah satu akibatnya, filsafat praktis moderen terus mengambil jarak dari konsensus metafisis dengan pandangan kodrati yang bersifat teleologis. Di samping itu filsafat praktis moderen juga menghindari pendasaran teologis atas kebenaran etis. Filsafat menarik konsekuensi politis-praktis dari proses demitologisasi dan sekularisasi konsep tentang manusia dan dunia tradisional.
Keempat, model kontrak sosial berbasis rasionalitas moral. Model ini deperkenalkan oleh dua fugur historis penting. Pertama, di satu sisi John Locke (1632-1704) mendasarkan teori kontrak sosial pada hukum kodrat Ilahi guna memberikan dasar legitimasi keberadaan negara. Sementara itu, di sisi lain, Immanuel Kant menjadikan imperatif kategoris hukum moral sebagai basis legitiasi keberadaan negara.
Baca Juga : Perempuan Korban Pelecehan Seksual Cenderung Bungkam, Mengapa?
Baca Juga : Profesionalisme Guru di Tengah Pandemi
Dalam Second Treatise of Government (1689), John Locke menguraikan konsep posisi alamiah sebagai suatu kondisi historis. Locke berpandangan bahwa manusia pada awal sejarah peradaban hidup dalam kondisi alamiah yang dilengkapi dengan hak-hak alamiah (hak asasi) yang diterimanya dari Tuhan. Akan tetapi pada masa itu tatanan hukum dan kekuasaan politik belum dikenal. Berdasarkan kehendak Allah, individu-individu tersebut memilik hak natural atas hidup, kebebasan dan milik. Dan hak milik berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh manusia.
Di samping itu pada posisi asali setiap individu dilengkapi dengan hak untuk membela diri serta hak untuk menghukum semua orang yang melanggar atau melecehkan hak tersebut. Potensi konflik yang muncul di antara individu menyebabkan kondisi hak-hak natural dalam posisi asali menjadi sangat rentan. Agar kepastian hukum guna melindungi hak-hak tersebut dapat terjamin, individu bersepakat untuk mendirikan negara atau pemerintahan. Di sini perlu diberikan catatan tentang perbedaan pandangan Locke dengan konsep negara Hobbes. Menurut Locke, pembuatan kontrak tidak berarti bahwa individu melepaskan hak-hak naturalnya dan menyerahkan kepada Leviathan seperti dianjurkan Hobbes. Hak-hak kodrati tetap berlaku, dan legitimasi negara justru diukur atas dasar kemampuannya untuk menjamin hak-hak tersebut.
Kedua, basis legitimasi keberadaan negara Immanuel Kant (1724-1804) dibahas dalam bukunya berjudul Rechtslehre (1797). Ia membangun argumentasinya sebagai berikut. Manusia di satu sisi adalah makhluk biologis (Naturwesen), namun di sisi lain memiliki akal budi. Di satu sisi manusia manusia juga tunduk pada sejumlah keterbatasan alamiah seperti kelangkaan sumber kekayaan (resources) dan tuntutan hidup bersama yang rentan terhadap konflik atau bahkan perang jika otoritas kekuasaan negara yang legitim tidak hadir. Namun di sisi lain manusia juga memiliki hak kodrati yakni hak asasi atas kebebasan dalam pengertian sebagai kebebasan dari kesewenang-wenangan (Willkűr) dari yang lain.
Situasi ini menciptakan konflik antara tuntutan perwujudan akan hak-hak dasar setiap manusia di satu sisi dan fakta ancaman kekerasan dalam kondisi posisi asali di sisi lain. Lebih dari itu, setiap individu dalam posisi asali memiliki hak sementara atas barang-barang yang tidak bertuan dalam masyarakat pranegara. Guna mengakhiri ketidakpastian hukum dalam posisi asali serta mengubah status kepemilikan sementara menjadi hak milik permanen, Kant mendesak terbentuknya kontrak agar status alamiah pranegara dapat ditinggalkan. Jadi menurut Kant, pembentukan negara merupakan tuntutan hak kebebasan dasar manusia dan tuntutan perlindungan hak milik yang adalah hak asasi manusia.
Baca Juga : Merawat Keindonesiaan
Baca Juga : Merosotnya Nilai-Nilai Antikorupsi di Tubuh KPK
Kelima, model komunitarian-intersubjektif. Bentuk lain dari legitimasi negara adalah model identitas sosial dan kultural sebuah bangsa seperti pernah dikembangkan oleh G.W.F. Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, negara adalah pemenuhan secara institusional dari apa yang dia namakan “Sittlichkeit”. Dalam filsafat politiknya, Hegel membuat distingsi yang tegas antara “Sittlichkeit” dari moralitas. Hegel berpandangan bahwa moralitas (dalam arti imperatif kategoris Kantian) menggambarkan sebuah struktur yang abstrak, formal, tanpa substansi dan tidak memberikan motivasi bagi para aktor.
Sementara itu, Sittlichkeit mengungkapkan konsep standar-standar normatif sebuah masyarakat yang berakar dan berkembang secara historis dan sosial (adat-istiadat). Dalam hubungan dengan ini, Hegel mengartikan negara sebagai sebuah ungkapan identitas yang bertumbuh secara sosial dan kultural. Tentu sebuah kekeliruan jika kita berpandangan bahwa Hegel dengan pandangannya sedang melegitimasi status quo sebuah tatanan politis. Juga Hegel tidak menyamakan begitu saja antara aspek genesis sikap moral dalam diri individu-individu dengan aspek validitas norma-norma tersebut.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya