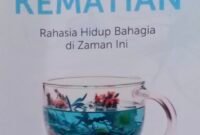
Review Buku | Senin, 4 Maret 2024 - 08:07 WITA
Indodian.com – Apakah ada kaitan antara kesadaran akan kematian dengan kebahagiaan? Tampaknya sulit menemukan jawabannya dalam buku-buku filsafat yang sudah ada sekarang ini. Tapi,…

Review Buku | Senin, 31 Oktober 2022 - 18:26 WITA
Judul : Perempuan di Titik Nol Penulis : Nawal El-Saadawi Penerjemah : Amir Sutaarga Penerbit : Obor Tahun terbit : 2002…
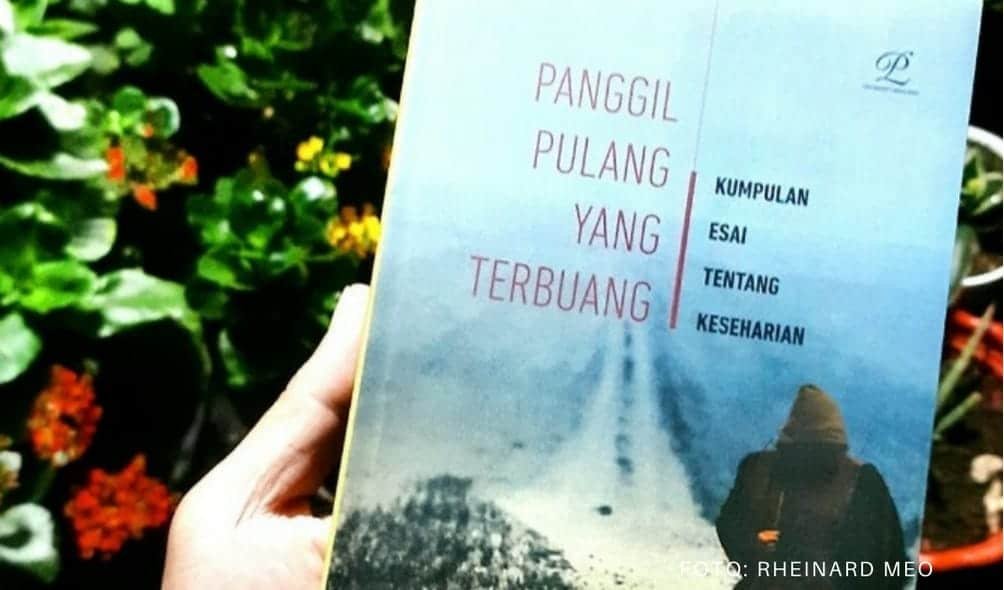
Review Buku | Jumat, 3 Desember 2021 - 00:22 WITA
Judul : Panggil Pulang yang Terbuang, Kumpulan Esai tentang Keseharian Penulis : Reinard L. Meo Penerbit : Penerbit Ledalero Tahun : Juli 2021 Setelah…

Review Buku | Rabu, 14 April 2021 - 13:54 WITA
Tulisan ini merupakan sebuah resensi novel Eleven Minutes karya novelis Brasil, Paulo Coelho. Keseluruhan bangunan resensi ini dibagi dalam empat pokok bahasan yaitu latar belakang penulisan novel, sinopsis, pesan dan kritikan.