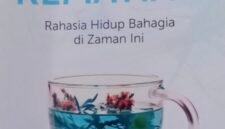Indonesia tengah mengalami paradigma perubahan dalam rangka membangun Indonesia baru, di atas komitmen religius dan humanis, keadilan, etika, demokrasi, HAM, setidak-tidaknya itulah yang saat ini kita perjuangkan. Pertanyaannya, akankah paradigma perubahan sekaligus membawa pergeseran nilai budaya pada warga bangsa kita? Jawabannya dilematis.
Perubahan tidak berarti ada mall, ada jalan toll, banyak hotel berbintang, mahasiswa menenteng hand phone baru, ada baju dan sepatu baru, jalan diaspal, banyak koruptor di tangkap, banyak kendaraan mewah berseliweran di jalan. Namun perubahan itu bisa juga diterjemahkan lain yakni seluruh sistem budaya mengalami kematian alias mandeg.
Kita boleh membangun mall, hotel mewah, jalan tol, namun sedikit diantara kita yang merasa prihatin dengan kemiskinan, stunting, kelaparan, keadilan, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, ini sama hal dengan kematian alias mandeg alias tidak maju. Atau lebih berdosa lagi, kita dengan gigih menyusun program anggaran pembangunan demi melegitimasi kebudayaan, tapi mutu kebudayaan tetap merosot, dengan kata lain menyusun program demi melegitimasi kebudayaan, tapi tetap tidak memelihara, sama dengan tidak maju alias mandeg.
Kendati kita sadar bahwa anggaran pembangunan yang kita terima dibiayai dari pinjaman luar negeri (hutang) yang pada akhirnya secara langsung atau tidak, terarah pada penciptaan dan pengekalan ketergantungan (dependecy of perpetuate ). Manifestasi dari kondisi seperti ini pembangunan cenderung tidak menjamah kepentingan kebudayaan dan bahkan menciptakan core area dan peripheral area di masing-masing daerah, serta tidak mendidik bangsa sendiri untuk mandiri.
Sadar atau tidak sebagai dampak pembangunan, warga bangsa kita saat ini telah terpisah menjadi tiga komunitas kasta baru (new caste community) yang berbeda tajam. Komunitas pertama adalah core society atau kasta inti (core caste ) dengan ciri-ciri: stabil/kuat ekonominya, terjamin masa depannya, memiliki akses kekuasaan cukup tinggi. Mareka yang masuk dalam kasta ini sebut saja komunitas sisa-sisa feodal (pejabat negara) dan mereka tetap haus akan kekuasaan, wanita, dan harta. Makanannya kebanyakan dari produk kapitalis.
Kedua, middle society atau kasta setengah pinggiran (semi peripheral caste) yakni, lahir dari masyarakat campuran antara sisa-sia feodal dan masyarakat idealis, dengan ciri-ciri menggantungkan diri pada idealisme, masyarakat rasional, mereka tidak membutuhkan penghargaan yang tinggi. Yang termasuk dalam kasta ini adalah para cendekiawan, kaum profesional, seniman, budayawan, rohaniawan, wartawan, penulis, jauh dari kekuasaan atau pengaruh, kesadaran politiknya tinggi, akses ke masyarakat cukup tinggi. Komunitas ini adalah orang-orang yang “berumah di atas angin“, (WS. Rendra, 1976), tidak mau terikat oleh suatu sistem yang menghalangi kebebasannya.
Ketiga, peripheral society atau kasta pinggiran (peripheral caste), yakni tidak stabil, mudah bergeser dari satu sektor ke sektor lain, cepat berpindah pekerjaan, tidak mempunyai idealisme, hidupnya sederhana, berani hidup sengsara, kehidupannya berlangsung dari tangan ke mulut, makanannya dari produk lima jarinya. Namun mempunyai andil besar terhadap politik dan kekuasaan (contohnya pada waktu pemilu atau pilkada). Komunitas ini kita namakan saja “masyarakat apung”. Mereka adalah kelompok yang besar jumlahnya. Mereka ini sebenarnya adalah sasaran pembangunan. Sebagian dalam komunitas ini adalah petani yang menyiapkan makanan bagi negara ini. Namun mereka tidak pernah diperhatikan oleh negara. Tidak mendapat subsidi sedikitpun. Mereka mempunyai tanggungjawab besar terhadap bangsa dan negara ini.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya