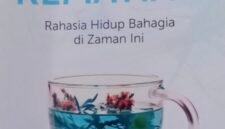Tidak perlu dipersoalkan wujud eksoteris agama yang dipeluk manusia. Sebab apa pun wujudnya, penemuan dan penerimaan manusia terhadap agama pasti berawal dari kenyataan “misteri yang menggentarkan” (mysterium tremendum), dan “misteri yang memesonakan” (mysterium fascinans).
Dalam semua agama yang dipeluk manusia, baik yang melalui proses budaya maupun wahyu, bisa dipastikan terobsesi dengan kedua hal tersebut. Hal itulah yang membuat manusia memandang agama sebagai sesuatu yang demikian bermakna, tidak saja bagi dirinya sebagai makhluk pribadi, tetapi juga bagi kehidupan kolektifnya dengan komunitas manusia lainnya. Berikutnya, agama secara sosiologis menjadi identitas kelompok yang sulit dihilangkan.
Ada kecenderungan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan manusia secara berkelompok yaitu, manusia selalu mengidentifikasi dirinya dengan agama kelompoknya. Kecenderungan lain setelah agama mengalami eksternalisasi dan objektivikasi sebagai realitas kelompok, pada masing-masing anggota kelompok selalu menjaga eksistensi kelompoknya terutama jika ada penetrasi dari kelompok lain. Selalu saja muncul kecurigaan atau prasangka terhadap kelompok lain.
Dan, tidak bisa dipungkiri, agama merupakan salah satu bagian dari prasangka. Prasangka itu, misalnya, tampak pada penilaian subjektif bahwa agama lain sebagai ancaman. Phobia terhadap keberadaan kelompok agama lain pun bersemai. Semua prasangka itu muncul dari pemahaman subjektif, tanpa perlu melakukan pemahaman secara fenomenologis. Meminjam ungkapan Walter Lippman: We do not first see, and then define, we define first and then see. Nah, konflik realistik dalam kehidupan agama bermula dari situasi pemahaman seperti ini.
Salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruksi yang lebih bersimpati dan berempati terhadap keberadaan agama lain adalah pendidikan. Kita tentu sangat bergembira dengan munculnya usaha-usaha konstruktif untuk semakin mendekatkan jarak sosial (social distance) antarkelompok agama.
Kegiatan dialog lintas agama sebagai salah usaha yang konstruktif tersebut, perkembangannya cukup menggembirakan belakangan ini. Tetapi tetap saja ada kritik terhadap usaha tersebut. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan dialog lintas agama hanya terbatas pada kalangan tertentu, yaitu kalangan elitenya saja. Seringkali pula tema-tema yang didialogkan kurang sistematis. Sudah saatnya institusi pendidikan dimanfaatkan sebagai tempat persemaian untuk menumbuhkan sikap egaliter terhadap keberadaan agama lain.
Dalam institusi yang memang sudah teruji ini, perlu dikembangkan pembelajaran agama bercorak multicultural inklusif yang dimulai sejak anak dini usia. Sejatinya, pendidikan sendiri seperti dikatakan oleh Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn dalam bukunya, Multicultural Education in a Pluralistic Society (2002), merupakan kegiatan yang bercorak multikultural inklusif mengingat beragamnya latar belakang warga belajar.
Di beberapa negara maju seperti USA, pendidikan multikultural telah dijadikan sebagai strategi dalam menanamkan sikap egaliter terhadap keberadaan kelompok lain. Ini agak berbeda dengan praktik pendidikan di tempat kita. Istilah multikulturalisme sendiri baru berkembang dalam satu dasawarsa terkahir ini. Sedangkan di Barat, konsep multikulturalisme telah berkembang pada 1920-an.
Ruang kita amat terbatas untuk mendiskusikan pengertian multikulturalisme yang memang sangat beragam. Penulis mencukupkan pada pengertian dari Watson (2000) bahwa, multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.
Tekanan multikulturalisme dalam definisi Watson terhadap penghargaan dan kesetaraan di tengah-tengah keragaman, bisa kita transfer ke dalam pembelajaran agama di sekolah. Maka gagasan pembelajaran agama bercorak multikultural, bisa dipahami sebagai suatu proses penyadaran terhadap adanya keanekaragaman agama serta kesediaan memberlakukan setiap agama secara egaliter.
Dalam pembelajaran agama bercorak multikultural, seluruh warga belajar diajak menghayati secara fenomenologis keragaman agama di luar agama yang dipeluknya. Dalam rangka itu, para warga belajar diberi penguatan agar bisa mentransformasikan pengalaman agamanya yang subjektif, ke pengalaman agama yang disebut Hasan Askari (1991) dengan subjektivitas ganda (double-subjectivism). Dalam subjektivitas ganda, pengalaman masing-masing pribadi coba didialogkan untuk bersama-sama mencari titik temu (modus vivendi). Tentu saja, pembelajaran agama yang diharapkan bisa mendorong tumbuhnya pengalaman subjektivitas ganda, harus bertitik tumpu pada landasan teologi dan filsafat tentang kesetaraan agama.
Kita tentu bisa berharap, jika pendidikan bisa digarap serius sebagai media untuk menumbuhkan sikap egaliter terhadap semua agama, maka keragaman agama bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber perdamaian sebagaimana ditekankan oleh Paus Fransikus.
*) Ben Senang Galus, penulis buku, Kosmopolitanis Satu Negeri Satu Jiwa, tinggal di Yogyakarta
Halaman : 1 2