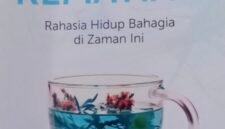Ikhtiar Bersama
Uraian pemikiran ketiga tokoh tersebut tetap tidak menyudahi perdebatan tentang ‘asal usul mental koruptif manusia Indonesia’. Namun, sekurang-kurangnya ketiga pemikir tersebut menyepakati tiga alasan umum yang menjadi akar bagi tumbuhnya mental koruptif manusia Indonesia, yaitu budaya hidup masyarakat itu sendiri, warisan budaya politik kolonial, dan sistem sosial-politik yang memang korup. Bagaimana keluar dari perangkap korupsi?
Menurut Mochtar Lubis, pemberantasan korupsi mesti bermula dari transformasi budaya. Lubis menganggap langkah tegas pemberantasan korupsi di RRC sebagai prototipe. Ia menulis:
Pada tahun 1951, di sana [RRC] dilancarkan kampanye besar-besaran tiga anti: antikorupsi, antipemborosan, dan antisikap birokrasi yang kaku. Lalu disusul dengan gerakan masyarakat yang melancarkan lima anti: antisogok-menyogok, antitipu daya menghindari pembayaran pajak, antipenipuan, anti mencuri milik negara, dan antipembocoran rahasia ekonomi negara (Lubis, 1985: xxi).
Secara singkat, menurut Mochtar Lubis, akar korupsi itu ada dalam budaya birokrasi-patrimonial yang telah merasuki tatanan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Sebab itu, mengharapkan perubahan pada tatanan tersebut tanpa tranformasi nilai budaya yang hidup di baliknya merupakan suatu kemustahilan. Produk hukum boleh bertambah banyak, tetapi jika lembaga penegak hukum tetap berjiwa patrimonial, korupsi tetap berjalan.
Dalam hal ini, pandangan Mochtar Lubis sejalan dengan Samuel P. Huntington. “The multiplication of laws thus multiplies the possibilities of corruption. … Hence in a society where corruption is widespread the passage of strict laws against corruption serves only to multiply the opportunities for corruption” (Huntington, “Modernization and Corruption”, 2007: 253-254). Mungkinkah korupsi tuntas hanya dengan tranformasi budaya baik budaya politik, sosial, maupun hukum?