Bola matanya buah matoa. Pometia pinnata yang nyata. Senyum sumringah menghiasi sudut bibirnya ketika melihat tumpukan uang di genggamanku. Sesekali tertawa. Gugusan giginya bagai biji mentimun. Memagar di celah-celah atap langit dan bumi.
Kami pun sepakat bahwa informasi dari beliau adalah privasi. Kami berbagi cerita satu sama lain. Tujuanku kemari memang bukan untuk bercinta. Bukan sayang.
“Apa yang mau saya jawab?”
“Ya, semuanyalah. Kalau boleh.”
Dia tercenung. Matanya tertuju ke langit-langit kamar. Bola matanya menyimpan masa, dimana dia memasuki surga dan neraka dunia
Baca Juga : Musisi Difabel Mata ini Ingin Memiliki Keyboard dan Membuka Kursus Musik
Baca Juga : Perempuan, Iklan dan Logika Properti
Dia berkisah bahwa menjual keindahan tubuh pada pria-pria berduit di tempat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Bukan untuk trend hedonistis, sosialita, selegram, atau selebvlog. Semata untuk mempertahankan hidup semenjak ditinggal yatim piatu setahun lalu.
Hidup di ibu kota memang serba uang. Tak ada uang tak bisa hidup. Ongkos rumah indekos seukuran ruang kelas saja dia harus menghabiskan satu sampai dua juta saban bulan.
Dia juga harus membeli beras seharga enam belas ribu untuk makan dua kali sehari. Kalau pun makan di warung, berarti membutuhkan lima puluh hingga seratus ribu per porsi. Belum terhitung perlengkapan make up dan biaya studi yang pada akhirnya mandek di semester ketiga.
“Hmmm, pusing juga memikirkan hidup ini.”
“Nona, apakah tidak ada cara lain? Maksud saya mungkinkah bekerja sebagai pramu hotel, restoran, atau penjaga toko?”
“Hmm, bagaimana mau kerja kalau kita distigma tak bermoral?”
“Hushhh.”
Sedang kami mengobral obrolan, lampu-lampu jalan di sudut kota terang-benderang. Gemerlap. Kota ini mendekap hangat dua zat bernyawa. Namun, dia tinggal di sebuah gang sempit. Berdampingan dengan Sophisticated. Lampu-lampu kota masih malu-malu menerangi lorong berpenduduk kelas menengah ke bawah seperti Pelangi.
Lampu-lampu dan lampion Sophisticted menjadikan kontrakannya jelas terbaca. Tapi saya nyaris tak melihat sejumlah pria berdasi menghampiri para bidadari di sini.
Persis saat yang sama seorang pria dengan setelan neces memasuki kamar. Tapi berdiri saja di pintu begitu tahu kami sedang berduaan.
Mereka berpapasan. Senyum manja terlintas dari parasnya. Entah apa yang dibicarakan. Tapi dari gestur tubuh dan mimiknya, mereka sedang menawarkan harga. Begitu pas harga tancap gas.
Baca Juga : “Utang Budi” Pater Thomas Krump, SVD
Baca Juga : Kain Songke dan Kenangan tentang Ibu
Saya penasaran. Lalu membongkar adegan sedetik itu melalui Pelangi.
“Aman?”
“Terkendali kak.”
“Baiklah. Lanjutkan!”
“Mereka adalah orang-orang yang familiar di media massa, tempat publik, dan kerap menjadi polisi moral,” katanya.
“Begitu kah?”
“Iya, tapi di sini mereka kalah sama lendir.”
“Astagnagaa!!”
Lalu siapa gerangan yang membuat anak ini di sini? Ah, nanti sajalah kutanya.
Pemilik rambut sebahu dan senyuman manis itu berpaut tiga tahun. Artinya dia yunior.
Saya ingat betul bagaimana dengan lugunya dia memperkenalkan diri kepada para senior ketika masa kuliah. Bahkan ketika tatapannya mendarat pada kepribadianku, yang ketika itu dipanggilnya Kak Senior.
Tapi kenapa dia di sini? Kenapa Tuhan? Dia kan teman kuliahku.



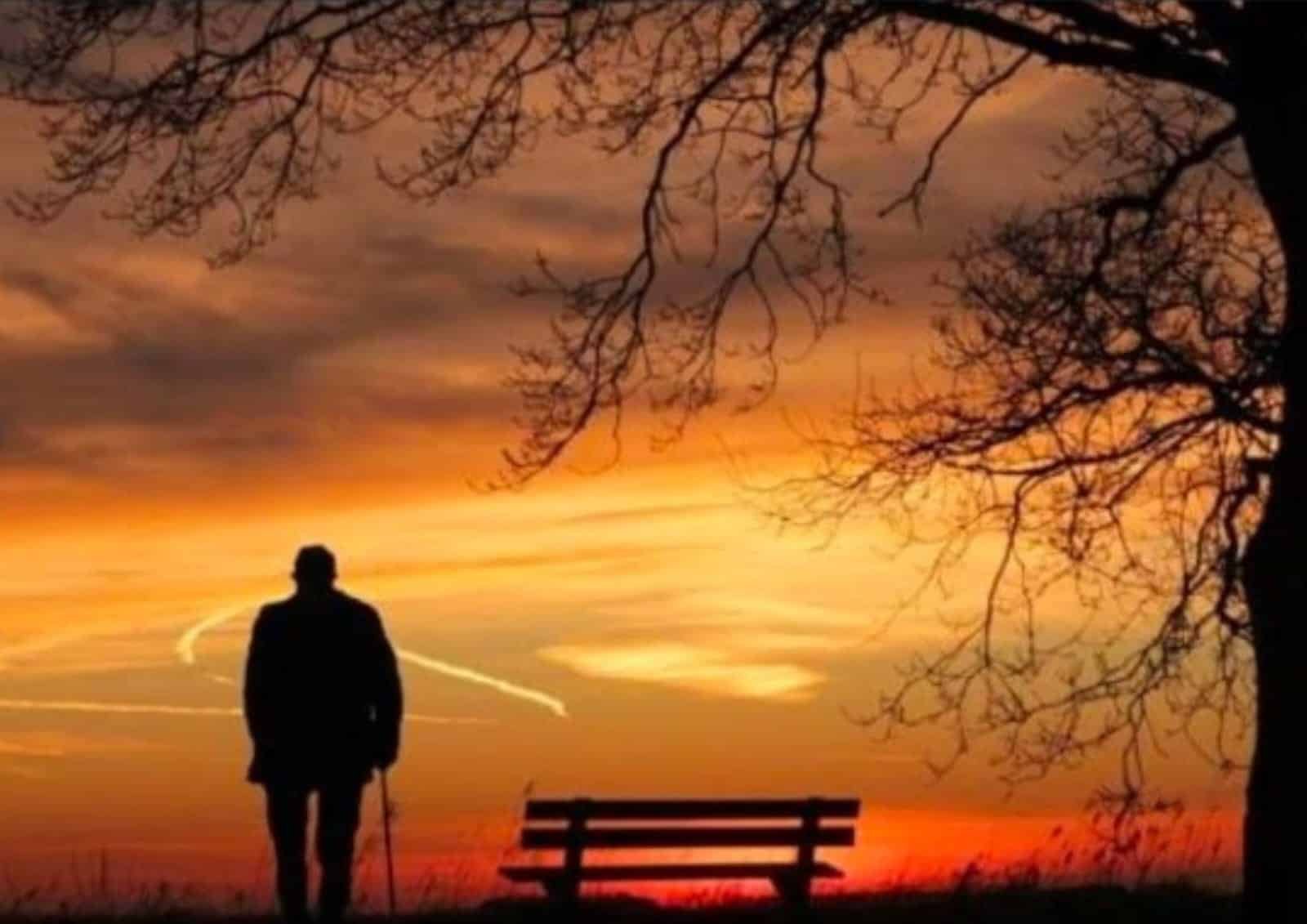








https://ott-ip.com/search?type=shopping&sort=time_desc&keyword=희윤이질사임신먹버남