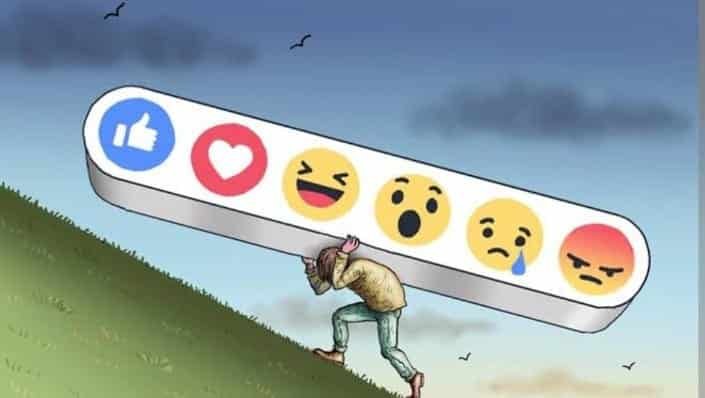
Filsafat | Selasa, 13 Juni 2023 - 16:26 WITA
Indodian.com – Teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, mengajar, menasehati, berkhotbah, memberi kuliah, berdagang, bertransaksi, dan bertahan hidup sejak beberapa dekade lalu. Kita berkomunikasi, mengikuti…
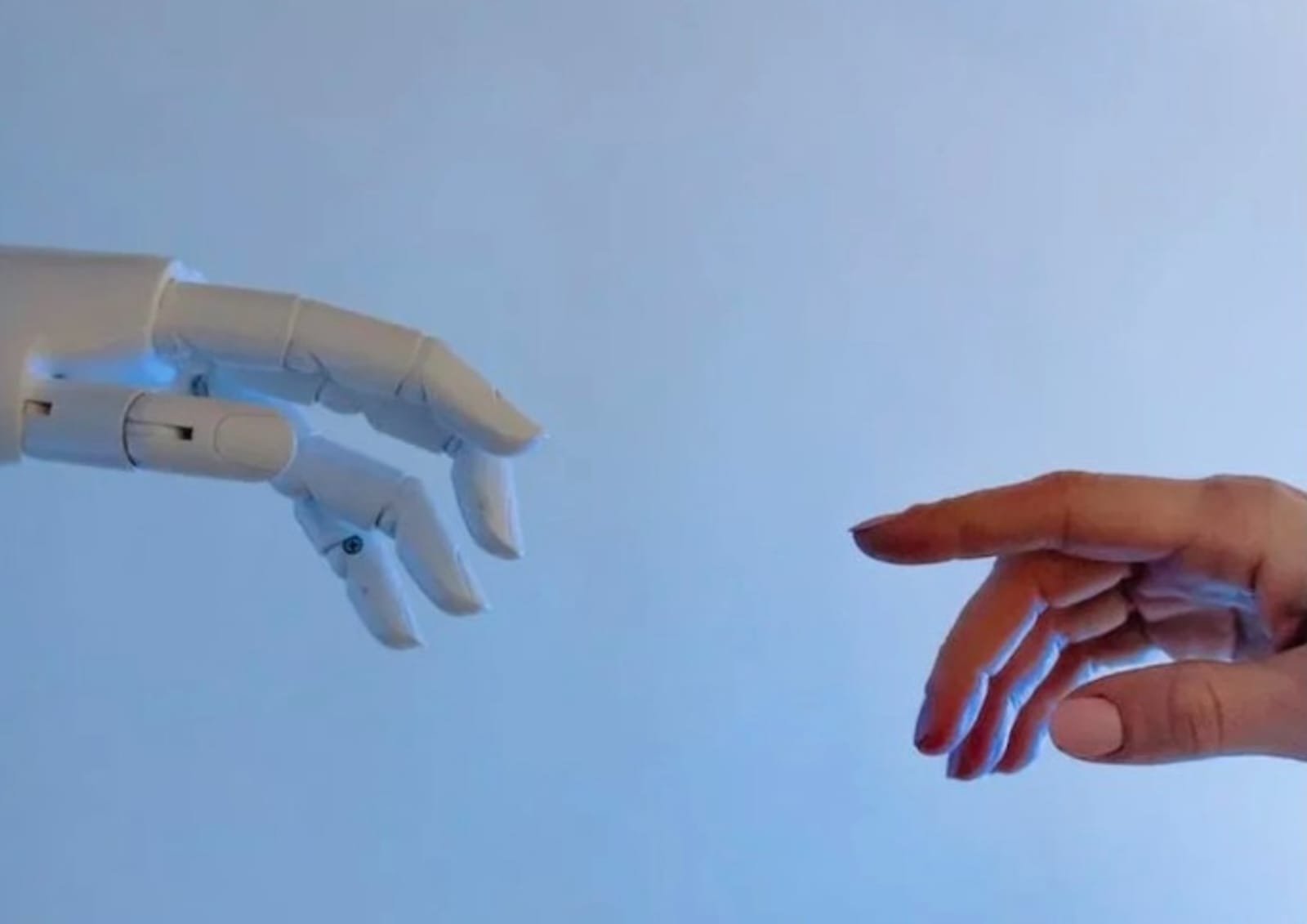
Filsafat | Rabu, 10 Mei 2023 - 21:40 WITA
Indodian.com – ChatGPT sedang masuk ke dalam ranah diskusi publik akhir-akhir ini. Kekuatan yang ditawarkan oleh ChatGPT sangat besar, dan jutaan orang dari seluruh…